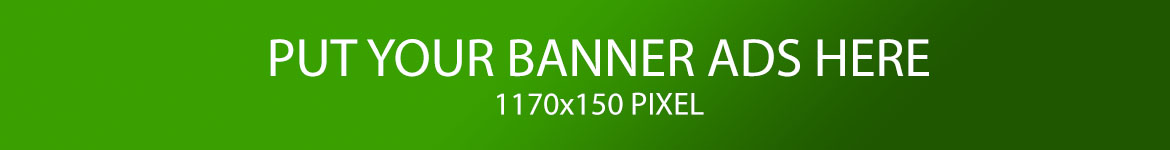- Selasa, 20 Januari 2026

Oleh: Yokhebed Arumdika Probosambodo, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Peristiwa penyerangan terhadap aparat Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, menjadi tamparan keras bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Di tengah tugas mulia memberantas jaringan peredaran narkotika, aparat justru menghadapi perlawanan brutal dari masyarakat setempat, sebagian di antaranya diduga menjadi bagian dari ekosistem gelap narkoba itu sendiri. Fenomena ini bukan sekadar “bentrok”, tetapi refleksi dari masalah sosial dan hukum yang jauh lebih kompleks.
Secara normatif, tindakan aparat penegak hukum dalam penggerebekan narkoba telah memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian pula UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi legitimasi bagi BNN dan Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika.
Namun, ketika aparat diserang oleh warga yang seharusnya menjadi pihak yang dilindungi, muncul pertanyaan serius: apakah ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat telah sedemikian besar, ataukah warga telah terkooptasi dalam jaringan narkoba itu sendiri?
Secara hukum pidana, perlawanan terhadap aparat dalam menjalankan tugasnya termasuk tindak pidana melawan pejabat yang menjalankan tugas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 212 dan 214 KUHP. Tindakan menyerang aparat jelas dapat diancam pidana penjara hingga tujuh tahun. Namun demikian, penegakan hukum tak cukup hanya dengan memproses pelaku perlawanan secara represif. Pemerintah dan aparat perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif untuk menumbuhkan kembali rasa percaya publik terhadap penegakan hukum, terutama di wilayah yang rawan dan termarjinalkan.
Kampung Bahari bukan satu-satunya kawasan yang dikenal sebagai “zona merah narkoba”. Fenomena serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain di Jakarta, Medan, dan Surabaya, di mana kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan menjadi lahan subur bagi peredaran narkotika. Dalam konteks ini, perang melawan narkoba tidak bisa hanya bersenjata hukum dan peluru, tetapi juga harus diiringi dengan kebijakan sosial yang menyentuh akar masalahnya.
Penegakan hukum yang efektif menuntut integrasi antara pendekatan pidana dan kebijakan sosial. BNN dan Polri perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil. Program rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi bahaya narkoba harus berjalan paralel dengan operasi penindakan.
Lebih jauh, kebijakan criminal justice system juga harus menjamin bahwa tindakan hukum terhadap pelaku, termasuk warga yang menyerang aparat, dilakukan secara proporsional dan adil. Hukum pidana bukan alat balas dendam, tetapi instrumen untuk memulihkan ketertiban dan kepercayaan sosial. Serangan terhadap aparat di Kampung Bahari menjadi pengingat keras bahwa pemberantasan narkoba bukan sekadar tugas aparat, melainkan ujian bagi kesadaran hukum masyarakat. Ketika warga menolak atau bahkan menyerang aparat yang datang untuk membersihkan lingkungannya, itu menandakan krisis sosial yang dalam.
Polri dan BNN tidak boleh mundur. Namun, di saat yang sama, negara harus hadir bukan hanya dengan tameng dan senjata, tetapi juga dengan empati, edukasi, dan solusi. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan upaya pemulihan sosial. Hanya dengan demikian, “perang melawan narkoba” benar-benar menjadi perang untuk kemanusiaan, bukan sekadar operasi keamanan. (***)